Otentisitas Hadis Dalam Pandangan Al-A'zami Dan Orientalis
Oleh: Sang Misionaris
Pendahuluan
Setelah orientalis berhasil menjadikan Alkitab sebagai objek bulan-bulannya kajian mereka, di mana pada akhirnya mereka pun mencampakkan dan menegasikan adanya otentisitas dan validitas di dalam Alkitab. Mereka pun akhirnya beralih kepada persoalan kodifikasi Al-Qur’an, namun karena sulitnya keyakinan kaum Muslimin untuk diruntuhkan, akhirnya kajian mereka pun beralih kepada hadis, yang menjadi sumber kedua umat Islam, bahkan mereka pun mengotak-atik syarat otentisitas hadis yang telah dibentuk secara mapan oleh para ahli hadis. Karena orang Kristen mula-mula tidaklah memiliki aturan dan metode yang bisa diuji dalam membuktikan adanya otentisitas dan validitas di dalam Alkitab, tentu saja sikap mereka terhadap Alkitab memiliki keseragaman dalam menegasikan Alkitab sebagai Firman Tuhan. Namun, saat mereka beralih dalam mengkaji persoalan tentang penyusunan dan penulisan hadis, di antara mereka telah terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Lalu, metode apa saja yang bisa membuktikan bahwa hadis yang saat ini diterima oleh kaum Muslimin memiliki kesamaan dan keaslian, sebagaimana halnya yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad ﷺ? Seperti apa contoh perbedaan pendapat di kalangan para orientalis terkait penyusunan dan penulisan hadis? Dan seperti apakah otentisitas hadis dalam pandangan al-A'zami dan orientalis?
Pencatatan dan Pembukuan Hadis
Menurut al-A’zami, penulisan hadis sudah ada sejak masa awal Islam. Ia menegaskan bahwa 52 orang sahabat telah memiliki catatan hadis sejak masa Nabi Muhammad ﷺ. Bahkan, dalam beberapa kesempatan Nabi ﷺ telah mendiktekannya secara langsung hadis-hadis beliau kepada mereka. Selain itu, al-A’zami pun menekankan bahwa aktifitas tulis menulis telah menjadi tradisi sejak masa Jahiliyah dan menjadi salah satu unsur kesempurnaan seseorang, di mana hal tersebut dibuktikan dengan dituliskannya syair-syair milik para tokoh mereka, mencatat cerita perang, dan kata-kata mutiara dari para pujangga. Selain itu, pada masa pra-Islam pun telah ada tempat-tempat yang dijadikan sebagai majelis pendidikan di Jazirah Arab, seperti Mekkah, Thaif, Madinah, Anbar, Jirah, dan Daumat al-Jandal.
Pada masa Nabi ﷺ telah tampak adanya aktifitas tulis-menulis yang terus mengalami keberlangsungan, seperti menuliskan hutang-piutang, mencatat perjanjian, dokumen-dokumen dan sumpah, silsilah dan keturunan, dan lain-lain. Bukti lain adanya tulis-menulis yang telah membudaya di kalangan para sahabat ialah adanya sekretaris Nabi ﷺ yang berjumlah 61 orang, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Hanya saja kebanyakan dari mereka hanya menulis masalah-masalah yang khusus, sehingga ada yang menulis Al-Qur'an saja, seperti Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan lain-lain. Sedangkan para sahabat yang menulis secara khusus tentang harta-harta shadaqah adalah Zubair bin Awwam. Adapun para penulis masalah hutang dan perjanjian-perjanjian lain adalah Abdullah bin Arqam dan al-‘Ala ibn Uqbah, dan sahabat yang menuliskan tentang tafsiran kurma serta nama-nama orang yang masuk Islam adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Selain itu, al-A’zami pun menuturkan bahwa seperempat abad setelah Nabi ﷺ wafat, di Madinah telah ada gudang kertas yang berhimpitan dengan rumahnya Utsman bin Affan. Begitu pun kata kertas (qirtas, qaratis) telah disebut-sebut dalam peristiwa terbunuhnya Amr ibn Said al-Asydaq pada tahun 69 H, dan menjelang akhir abad ke-1 H, pemerintah Islam telah membagi-bagikan kertas kepada para gubernur.
Seorang orientalis, yang bernama Fuat Sezgin, meyakini bahwa koleksi hadis klasik yang dikumpulkan pada abad ke-3 H adalah hasil dari sebuah proses periwayatan yang terpercaya atau kelanjutan dari proses kegiatan tertulis yang telah dipraktekkan oleh para sahabat sejak masa Nabi ﷺ. Di sini, pendapat Fuat Sezgin berbeda dengan pendapatnya Ignaz Goldziher. Ignaz tidak menolak kemungkinan bahwa para sahabat telah berusaha menyimpan kata-kata dan perbuatan Nabi ﷺ, yang disebut dengan shahifah, dan penggunaan isnad berawal ketika para sahabat menyampaikan kepada generasi selanjutnya atas apa yang telah mereka dengar. Namun demikian, Ignaz mempertahankan adanya kemungkinan bahwa shahifah-shahifah tersebut merupakan penemuan yang telah dibuat oleh generasi belakangan untuk memberikan pembenaran bagi shahifah-shahifah yang muncul di kemudian hari untuk melawan mereka yang telah menentang adanya penulisan hadis, dan juga pemalsuan hadis. Pendapat Ignaz tersebut ditentang oleh Sezgin dengan mengutip laporan-laporan dari sumber awal Muslim, seperti ‘Ilal karya Ahmad bin Hanbal, Thabaqat karya Ibnu Sa’ad, Tarikh karya al-Bukhari, Taqdiman karya Ibnu Abi Hatim, Taqyid Al-‘Ilm karya Ibnu Abdul Barr dan lain-lain. Sezgin telah secara konsisten membuat penilaian historis terhadap koleksi hadis, yang argumentasinya itu didasari dari literatur Muslim. Bahkan, selain mengakui adanya kegiatan tulis-menulis pada masa az-Zuhri telah matang, ia pun mengakui pula bahwa pada beberapa pemerintah Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, agar materi-materi hadis tidak hilang ia memerintahkan untuk mengumpulkannya dalam bentuk yang resmi.
Tidak hanya Sezgin yang memiliki pandangan positif tentang adanya tradisi pembukuan hadis di awal Islam, Nabia Abbot pun berpendapat yang sama seperti halnya Sezgin. Bahkan, ia mendukung adanya eksistensi aktivitas tulis-menulis di kalangan orang Arab bahkan sebelum masa Islam, dan juga mendukung pendapat tentang adanya tradisi penulisan hadis sejak masa Nabi ﷺ. Namun demikian, Abbot tidak berpendapat bahwa semua hadis yang terdapat pada kutub as-sittah memiliki keautentikan sepenuhnya. Tetapi hadis-hadis tersebut, menurut Abbot, memuat intisari yang murni dari perkataan dan perbuatan Muhammad ﷺ, para sahabatnya dan para tabi’in, yang direkam oleh az-Zuhri dan orang-orang yang sezamannya, yang pada gilirannya menerima pula dari para pendahulu mereka.
Berbeda dengan Sezgin dan Abbot, Schoeler menolak pandangan keduanya, bahwa periwayatan awal hadis tidaklah dibentuk oleh tulisan dalam bentuk buku, melainkan periwayatan hadis diriwayatkan secara lisan dan tulisan yang hidup secara berdampingan dan terkadang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dalam cara yang berbeda. Setelah Schoeler melakukan penelitian terhadap karakter periwayatan pada masa awal Islam, ia menyimpulkan, bahwa pada paruh kedua abad pertama hijriah, para tabi’in seperti halnya Urwah bin Az-Zubair telah menyibukkan dirinya dengan mengumpulkan laporan-laporan tentang Nabi, dan mereka sering memiliki catatan-catatan untuk mendukung hafalannya. Walau Schoeler memiliki pandangan bahwa sumber tertulis dapat dengan mudah dipalsukan, sebagaimana halnya materi lisan, namun ia berpendapat bahwa materi lisan dan tulisan saling melengkapi dan tidak berdiri sendiri.
Sama halnya dengan Schoeler, Harald Motzki pun mengambil posisi di tengah-tengah antara pihak Ignaz Goldziher dan Schacht dengan Sizgen dan Abbot, meskipun metode yang ia suguhkan berbeda dengan Sizgen. Dalam sebuah penelitiannya, Motzki memfokuskan dirinya pada Mushannafnya Abdul Ar-Razzaq Ash-Shan’ani (w. 211 H). Edisi karya tersebut, telah memuat sejumlah gabungan riwayat, tetapi 90 % materinya kembali kepada Ishaq bin Ibrahm Ad-Dabari (w. 285 H). Riwayatnya mengimplikasikan, menurut Motzki, sebuah teks tertulis. Dengan menggunakan pendekatan historis tradisi dalam analisisnya terhadap Mushannaf tersebut, ia menentang sejumlah pendapat orientalis seperti Glodziher dan Schacht yang menyangkut tentang perkembangan jurisprudensi Islam awal dan hadis-hadis hukum. Dengan memperhatikan struktur Mushannaf, Motzki berkesimpulan bahwa Abdul Razzaq telah menerimanya dari empat otoritas atau informan utamanya, yaitu Ma’mar; Ibnu Juraij; Ats-Tsauri dan Ibnu ‘Uyainah, adalah asli bahwa materi-materinya itu tidaklah dipalsukan oleh Abdul Razzaq.
Demi terjaganya keotentikan hadis, Nabi Muhammad ﷺ telah menggunakan 3 metode dalam mengajarkan hadis, seperti metode lisan; tulisan dan peragaan praktis, namun lain halnya dengan metode pengajaran hadis yang ditempuh oleh para ahli hadis di masa pasca sahabat. Di mana metode tersebut ditempuh dengan cara:
1. Mengajarkan hadis secara lisan. Metode ini sama dengan apa yang dilakukan pada masa Nabi ﷺ dan juga para sahabat, meskipun pada paruh abad ke-2 H memiliki sedikit perbedaan dalam cara pelaksanaannya, yaitu adanya kebiasaan para murid untuk tinggal bersama dengan gurunya dengan maksud untuk memperoleh hadis darinya. Selain itu, metode ini pun diatur pula sedemikian rupa, sehingga pada umumnya para guru tidak mengajarkan hadis terlalu banyak kepada para muridnya. Al-A’zami mengutip dari al-Baghdadi (396-463 H) dalam kitab al-Jami’ li akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami, bahwa Khalid al-Hazza (80-141 H) berkata, “Kami datang ke rumah Abu Qilabah, ketika beliau sudah mengajari kami tiga buah hadis, beliau berkata, ‘Tiga hadis itu sudah banyak.’” Selain itu, ada pula riwayat dari Ibn ‘Ulayyah (100-193 H) yang berkata, “Saya hanya mendengar lima buah hadis dari Ayyub (66-131 H0. Seandainya ia mau mengajarkan lebih banyak, maka saya tidak ingin menambahnya.”
2. Membaca hadis dari suatu kitab. Dalam metode ini ada 3 macam, yaitu (1) Guru membacakan kitabnya sendiri, sedangkan muridnya hanya mendengarkannya saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Hanbal (164-241 H), Zuhair Ibn Muhammad (w. 258 H), dan Abdullah ibn al-Mubarak (118-181 H). (2) Guru membacakan kitab orang lain, sedangkan muridnya hanya mendengarkannya saja. Adapun kitab yang dibacakan itu pada umumnya adalah kitab gurunya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Aban ibn Abu Ayyasy (w. 138 H), Abdul Malik Ibn Abdul Aziz ibn Juraij (80-150 H), dan Jarir ibn Hazim (90-175 H). (3) Murid membacakannya di hadapan gurunya. Cara ketiga ini pernah dilakukan oleh Ibn Mubarak (118-181 H), Ibnu Mahdi (w. 198 H), Jarir Ibn Abdul Hamid (110-188 H), dan Ma’mar ibn Sulaiman (w. 191 H).
3. Metode tanya jawab. Sistem atraf, yaitu menuliskan pangkal hadisnya saja, digunakan pula dalam pengajaran hadis dengan menggunakan metode tanya jawab. Dalam metode ini, murid membacakan pangkal hadis, kemudian gurunya sendiri meneruskan hadis tersebut secara lengkap. Al-A’zami telah mengutip suatu riwayat dari kitab al-‘Ilal wa Ma’rifah ar-Rijal, karya Ibn Hanbal, bahwa Ibn Sirrin (23-110 H) berkata, “Saya bertemu Ubaidah dengan membawa kitab atraf hadis, lalu kutanyakan hal itu kepadanya.”
4. Metode imla. Metode ini sejatinya telah dipraktekkan sebelumnya oleh Nabi Muhammad ﷺ ketika beliau masih hidup, yang selalu terbiasa mendiktekan isi perjanjian, dokumen, dan hadis-hadis kepada para sahabatnya. Adapun ahli hadis yang menggunakan metode imla adalah Syu’bah ibn al-Hallaj (83-160 H), Yazid ibn Harun al-Wasiti (117-206 H), Asim ibn Ali (w. 221 H), Amr ibn Marzuq al-Bahili (w. 224 H), Abu Bakar ibn Ayyasy (96-194 H), Abu Bakar ibn Abu Sabrah (100-162 H), Hasan al-Bashri (21-110 H), az-Zuhri (50-125 H), Syahr ibn Hausyab (w. 113 H), dan Ikrimah ibn Ammar (w. 159 H).
Selain itu, menurut al-A’zami, bahwa pada masa abad ke1 hingga awal abad ke-2 H, telah ada beberapa orang ahli hadis yang menulis hadis, namun setelah ia hafal, maka hadis-hadis itu pun kemudian dihapusnya, seperti yang dilakukan oleh Masruq ibn al-Ajda’ (w. 62/63 H), Muhammad ibn Sirin (23-110 H), Khalid al-Hazza (80-141 H), dan Hisyam ibn Hassan (w. 148 H). Sebaliknya, ada pula yang menghafalkan hadis terlebih dahulu, lalu menuliskannya, seperti yang dilakukan oleh al-A’masy (61-147 H), Khalid ibn Yazid al-Jumahi (80-139 H), Sufyan as-Sauri (97-161 H), Hammad ibn Salamah (w. 167 H), Abdul Waris al-Anbari (w. 180 H), Abdullah Ibnu Idris (w. 192 H), dan Sulaiman ibn Harb (144-224 H). Adapun alat tulis yang sering mereka gunakan dalam mencatat hadis terutama pada abad ke-2 H adalah kepingan-kepingan papan tipis dan dedaunan, lalu setelah itu mereka menyalinnya kembali ke dalam kertas.
Validitas Isnad
Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang sampai kepada kita, semuanya telah melalui mata rantai periwayatan atau isnad, di mana sistem isnad yang ada telah memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kredibilitas sumber dalam periwayatan dan pengajaran hadis. Permulaan sistem isnad telah ada sejak masa Nabi Muhammad ﷺ yang terus mengalami perkembangan menjadi sistem yang mapan pada akhir abad ke-1 H, dan selama dekade ke-4 dan ke-5, sistem isnad telah memainkan peranan yang sangat penting untuk menyeleksi hadis-hadis palsu dari hadis-hadis yang shahih, sebagai akibat dari terjadinya pergolakan politik saat itu yang membuka peluang-peluang besar untuk melakukan pemalsuan hadis. Oleh karena itu, para ulama menjadi berhati-hati dan mulai melakukan penelitian sumber-sumber informasi yang diberikan kepada mereka, sebagaimana yang tampak dalam ucapan Ibnu Sirin (23-110 H), “Mereka sebelumnya tidak terbiasa menanyakan isnad, tetapi ketika terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Berikan kepadaku nama-nama para informan yang engkau miliki.’ Jika mereka termasuk ahli sunnah maka hadis mereka diterima, sedangkan jika mereka ahli bid’ah maka hadisnya mereka tolak.” Adanya pernyataan dari Ibnu Sirin tersebut menunjukan bahwa isnad telah ada sebelum Ibn Sirin hidup dan telah ada sejak abad ke-1 H, bahkan sebelum Islam datang sudah ada metode yang mirip dengan pemakaian sanad yaitu dalam menyusun buku, meskipun tidak ada kejelasan sejauh mana metode itu digunakan.
Validitas sistem isnad telah ditunjukkan dalam ribuan hadis dengan redaksi sama yang ditemukan di wilayah-wilayah yang berbeda, yang asal-usulnya dapat ditelusuri ke belakang hingga sampai kepada Nabi Muhammad ﷺ atau sahabat, atau tabi’in, bahwa isi dan susunan kata yang tersebar begitu luas memiliki kesamaan. Salah satu buktinya adalah contoh hadis tentang mencuci tangan sebelum tidur yang diriwayatkan oleh orang banyak, dan memiliki kesamaan isi dan susunan kata yang sama. Hadis tersebut, selain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, juga diriwayatkan pula oleh Umar, Jabir, Siti Aisyah dan Ali. Dari jalur Abu Hurairah, misalnya, hadis ini disebarkan oleh tiga belas muridnya: 8 orang dari Madinah, 1 orang dari Kufah, 2 orang dari Basrah, 1 orang dari Yaman, dan 1 orang lagi dari Syiria. Selanjutnya, ada 16 ulama yang telah meriwayatkan hadis ini dari murid-muridnya Abu Hurairah: 6 dari Madinah, 4 dari Basrah, 2 dari Kufah, 1 dari Mekkah, 1 dari Yaman, 1 dari Khurasan, 1 dari Syria. Az-Zuhri dan al-A’masy telah meriwayatkan hadis ini lebih dari satu sumber. Ibnu Hanbal mengabsahkannya paling tidak 15 kali dari Abu Hurairah.
Skema sanad dari hadis di atas telah menunjukkan betapa mudahnya pengetahuan hadis tersebut menyebar ke seluruh dunia Islam dan betapa cepatnya jumlah periwayat yang meningkat dalam setiap generasi. Semakin ke bawah suatu rantai periwayatan, maka jumlah periwayat akan semakin meningkat dan daerahnya semakin meluas dan terpencar-pencar. Hal tersebut menunjukkan adanya eksistensi sistem isnad di masa awal dan memperlihatkan betapa mustahilnya untuk memalsukan isnad dalam skala yang besar. Selain itu, yang perlu dicermati adalah bahwa tidak semua orang Madinah, Basrah, atau Kufah berguru pada satu orang. Namun demikian, Caetani dan Sprenger telah membantah adanya penggunaan sistem isnad di masa abad pertama hijriah, dan bahkan mereka meyakini bahwa sistem isnad yang terdapat dalam tradisi Islam telah dibuat oleh para ahli hadis pada masa abad ke-2 H.
Menurut Caetani, Urwah (w. 94 H) adalah orang pertama yang telah menghimpun hadits Nabi ﷺ, tetapi ia tidak menggunakan isnad dan tidak menyebutkan pula sumber-sumbernya selain Al-Qur’an, sebagaimana yang terdapat pada kitab Tarikh at-Thabari yang banyak mengambil sumber dari Urwah. Selanjutnya Caetani berpendapat, bahwa pada masa Abdul Malik (sekitar 70-80 H), yakni 60 tahun lebih setelah Nabi ﷺ wafat, penggunaan sanad dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi ﷺ juga belum dikenal. Dari sini, Caetani berkesimpulan bahwa pemakaian sanad baru dimulai pada masa antara Urwah dan Ibnu Ishaq (w. 151 H). Namun, al-A’zami membantah Caetani dengan menegaskan bahwa cuplikan-cuplikan yang bersumber dari Urwah, tidak saja terdapat pada kitab Tarikh at-Thabari, melainkan terdapat pula pada kitab lain yang justru lebih tua dari kitab Thabari, yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal, yang di mana di dalamnya Urwah telah menyebutkan sumber hadis yang ia riwayatkan, yaitu Aisyah. Selain Caetani, Sprenger pun berpendapat hal yang sama, bahwa tulisan-tulisan Urwah yang dikirimkan kepada Abdul Malik tidak menggunakan sanad.
Pendapat Caetani dan Sprenger, tidak saja dibantah oleh al-A’zami, melainkan mendapatkan pula bantahannya dari Horovitz, menurutnya, orang-orang yang mengatakan bahwa Urwah tidak menggunakan isnad itu sebenarnya mereka belum mempelajari kitab-kitab Urwah berikut sanad-sanadnya secara lengkap. Dan Horovitz pun berkesimpulan bahwa pemakaian sanad dalam meriwayatkan hadis sudah dimulai sejak sepertiga yang ketiga dari abad ke-1 H. Tidak hanya Horovitz, Robson pun memiliki pandangan yang sama, dan bahkan telah menyebutkan bahwa pada pertengahan abad ke-1 H, telah ada suatu metode semacam isnad. Sebab pada masa itu sejumlah sahabat sudah wafat, sedangkan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi ﷺ mulai meriwayatkan hadis-hadisnya. Selanjutnya Robson menyimpulkan bahwa: “Kita mengetahui bahwa Ibn Ishaq pada separuh pertama abad ke-2 H banyak menyebarkan ilmunya dengan tanpa sanad, sedangkan pengetahuan-pengetahuan yang masih tersisa padanya kebanyakan juga tanpa sanad yang lengkap. Orang-orang yang hidup sebelum Ibnu Ishaq tentu kurang memperhatikan masalah sanad dibandingkan Ibnu Ishaq sendiri. Namun demikian, kita tidak boleh mengatakan bahwa isnad baru dikenal pada masa az-Zuhri dan belum dikenal pada masa Urwah. Metode pemakaian sanad itu memang berkembang lamban dan sangat lama, sehingga pendapat yang mengatakan bahwa sejumlah sanad sudah dikenal sejak dulu mungkin dapat diterima.”
Metode Kritik Hadis
Kritik hadis merupakan aktifitas yang telah mentradisi di kalangan ahli hadis dalam menyeleksi kualitas hadis dan menentukan kredibilitas para periwayatnya. Selain itu, kritik hadis pun ditempuh untuk mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan yang bersifat manusiawi dalam menghafal dan mencatat hadis. Apabila kritik adalah usaha untuk membedakan mana yang shahih (benar) dari yang salah atau dhaif (lemah), maka dapat dinyatakan bahwa kritik hadis seperti itu telah dimulai pada masa hidup Nabi ﷺ. Akan tetapi, aktifitas kritik pada tahap ini tidak lebih dari menemui Nabi ﷺ untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi langsung dari beliau. Proses transfer informasi hadis di kalangan sesama para sahabat Nabi ﷺ cukup hanya berbekalkan kewaspadaan terhadap kadar akurasi pemberitaan. Kondisi daya ingat, ketepatan persepsi dalam menguasai fakta kehadisan di masa hidup Nabi ﷺ dan faktor gangguan indera mata itu saja yang perlu dicermati dampaknya. Karena sesama sahabat tidak pernah memiliki kecenderungan untuk saling mencurigai, baik dalam memberitakan sendiri setiap informasi hadis atau pun yang berasal dari sahabat lainnya.
Metode kritik yang dilakukan oleh para ahli hadis merupakan metode ilmiah, karena para ahli hadis telah mencermati dua aspek ketika akan melakukan kritik hadis, yaitu penelitian terhadap para periwayat (kritik sanad) dan juga melakukan penelitian terhadap kandungan hadis yang diriwayatkannya (kritik matan). Melalui karyanya, Studies in Hadith Methodology and Literature, al-A’zami menjelaskan lebih lanjut bahwa kritik dalam melakukan pengujian terhadap hadis-hadis sebelum diterimanya sebagai hadis yang valid, menurutnya, haruslah melalui tiga tahap pengujian, yaitu: karakter periwayat, perbandingan tekstual dan kritik nalar.
Kaidah keshahihan sanad hadis, melakukan pengujian karakter kepada para periwayat hadis, yang telah ditetapkan oleh al-A’zami tidaklah berbeda dengan kaedah keshahihan sanad yang ditetapkan para ahli hadis, yakni haruslah ditentukan dari adanya ittisal as-sanad, periwayat ‘adil dan dabit, terhidar dari syuzuz dan tidak adanya ‘illat. Al-A’zami menegaskan, bahwa karakter seorang periwayat hadis haruslah memenuhi syarat ‘adil dan dabit (memiliki kekuatan hafalan), karena suatu hadis tidak dapat dinyatakan shahih hanya dari aspek matannya saja, tetapi haruslah shahih dari segi sanadnya. ‘Adil dimaknai oleh al-A’zami sebagaimana para ahli hadis umumnya yaitu orang yang memiliki akhlak dan perilaku keberagamaan yang baik, dengan kata lain, adil yaitu orang Muslim, baligh, berakal, terhindar dari fasik, dan menjaga muru’ah (rasa malu, kemuliaan, dan kehormatan diri). Cara untuk mendapatkan ke’adilan seorang periwayat bisa diperoleh dengan cara melakukan penelitian terhadap buku-buku biografi untuk mengetahui data historis, mengecek dokumen, jenis kertas, dan tinta yang digunakan dalam penulisan. Cara demikian memang sulit untuk dilakukan, sehingga untuk mengecek kualitas periwayatan seseorang terpaksa mengandalkan pada laporan orang-orang yang hidup sezaman dengannya. Adanya sikap permusuhan atau kebaikan bisa mempengaruhi dalam rekomendasi yang diberikan, maka dari itu, dibutuhkan kecermatan dalam memberikan penilaian dan meneliti karakter periwayat, tanpa mengedepankan kebencian sehingga menghasilkan ketidakadilan dalam memberikan penilaian, di samping menggunakan pula pengujian pengetahuan sejarah dari para periwayat.
Adapun perbandingan tekstual atau perbandingan silang merupakan bagian dari aktifitas kritik matan yang bisa dilakukan dengan enam bentuk, seperti: membandingkan hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat yang berbeda, membandingkan pernyataan-pernyataan yang dibuat pada waktu yang berbeda oleh ulama yang sama, membandingkan hadis-hadis dari para murid yang berbeda tetapi berasal dari guru yang sama, membandingkan hadis yang diterima dari seorang periwayat dengan periwayat lain yang semasa dengannya, membandingkan hadis yang diriwayatkan secara lisan dengan versi tulisan, membandingkan hadis dengan teks yang berkaitan dalam al-Qur’an. Sedangkan kritik nalar yang diterapkan pada tiap tahapan dalam penelitian hadis, menurut al-A’zami, haruslah mencakup penggunaan rasio dalam hal: mempelajari hadis, mengajarkan hadis, menilai periwayat dan mengevaluasi otentisitas hadis. Al-Idlibi mengungkapkan, bahwa nalar atau rasio memiliki peran dalam kritik matan. Ini disebabkan karena hadis Nabi ﷺ tidak mungkin bertentangan dengan rasio. Adapun rasio yang dimaksud di sini adalah rasio yang tercerahkan dengan Al-Qur’an dan hadis yang shahih, bukan berdasarkan rasio yang murni, karena rasio yang murni tidak bisa menghukumi baik dan buruk. Selain itu, rasio pun tidak gegabah dalam menolak hadis-hadis hanya karena ada subhat ringan, dan tidak mudah menerima hadis yang tidak shahih dengan mengusahakan penakwilan yang mengada-ngada.
Kesimpulan
Adanya upaya agar kaum Muslimin di kemudian hari mendapatkan hadis yang sama, sebagaimana hadis yang telah diterima oleh para sahabat, seorang Nabi yang ummi, Nabi Muhammad ﷺ telah menjadi seorang pelopor dalam menjaga otentisitas hadis, di mana kondisi tersebut dibantu dengan adanya peran aktif para sahabat yang selalu kritis ketika mendapatkan suatu hadis yang tidak sama dengan yang sahabat lainnya. Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah para sahabat, tentunya mereka bisa secara langsung melakukan klarifikasi kepada Nabi, namun karena persoalan politik telah mengakibatkan terjadinya pemalsuan hadis dan Nabi ﷺ pun telah tiada, yang pemalsuan hadis tersebut terjadi setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka dengan penuh ketekunan dan kecermatan kaum Muslimin di kemudian hari, telah menghasilkan berbagai disiplin ilmu hadis yang secara ilmiah mampu membuktikan bahwa hadis yang diterima oleh kaum Muslimin saat ini, memiliki kesamaan dengan apa yang telah diterima oleh para sahabat di masa Nabi Muhammad ﷺ. Dan suatu hal yang wajar, jika sekiranya para orientalis pun mengalami perbedaan pendapat terkait awal mula hadis bisa terjaga dengan baik, apakah dengan cara lisan (hafalan), ataukah dengan tulisan ataukah dengan keduanya. Karena metode yang digunakan pada tradisi Islam, merupakan satu-satunya metode ilmiah yang kala itu belum pernah digunakan oleh negara dan kelompok manapun di dunia ini. Oleh karena itu, suatu hal yang absurd jika ada orang-orang Kristen yang menilai dan bahkan menyamakan hadis dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, khususnya Injil dan Surat-surat yang terdapat pada Perjanjian Baru. Karena keduanya memiliki perbedaan tradisi dan metode, tentunya apa yang dihasilkannya pun akan berbeda pula.
Artikel ini disarikan dari :
Amin, Kamaruddin. Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritis Hadis. Jakarta: Hikmah, 2009.
Farida, Umma. Kontribusi Pemikiran Muhammad Mustafa Al-A’Zami Dalam Studi Hadis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
Hasbi, Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy. Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
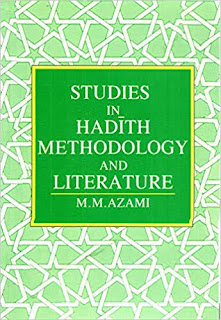
Comments
Post a Comment